PENCERAHAN KITAB KUNING
PEMBAGIAN KALIMAT DALAM BAHASA ARAB
Kalimat
terdiri dari 3 macam yaitu : isim, fi’il dan huruf
1. Isim adalah setiap kalimat yang menunjukkan
manusia, hewan, tumbuhan, benda, tempat, waktu, sifat, atau makna yang sepi
dari waktu.
Contoh : رجل, زيد, اسد, شهر, نظيف
Isim dapat dibedakan dengan lainnya dengan ketentuan :
-
Menerima tanwin contoh : رَجُلٌ, كِتَابُ, شَجَرَةٌ
-
Memungkinkan kemasukan al contoh : الرَّجُلُ, الكِتَابُ, الشَجَرَةُ
-
Memungkinkan kemasukan huruf nida (panggilan) contoh : يَا رَجُلُ, يَا مُحَمَّدُ
-
Memungkinkan dijerkan dengan huruf jer dan idlofah contoh :
عَلَى
شَجَرَةِ, غَصْنُ الشَّجَرَةِ
2. Fi’il adalah kalimat yang
menunjukkan terjadinya sesuatu dengan zaman yang tertentu, contoh : كَتَبَ fi’il
madli, يَجْرِيْ fi’il mudlori’, اِسْمَعْ fi’il amar.
Fi’I; dapat dibedakan dengan lainnya dengan ketentuan :
-
Memungkinkan kemasukan ta’ fa’il (ta’ sebagai pelaku)
contoh : كَتَبْتَ
-
Memungkinkan bertemu ta’ ta’nis contoh : كَتَبَتْ, تَكْتثبُ
-
Memungkinkan bertemu ya’ muhkotob contoh : تَكْتُبِيْنَ, اشْكُرِيْ
-
Mungkin bertemu dengan nun taukid, contoh : لِيَكْتُبِيْنَ, اشْكُرْن
3. Huruf adalah kalimat yang tidak
memiliki arti tanpa bersamaan dengan lainnya, contoh : في, أن, هل, لم
Isim dari segi I’rob dan mabni
Isim mu’rob
adalah perubahan akhir kalimat karena kemasukan amil didalammnya.
I’rob
terbagi menjadi 3, yaitu : rafa’ nashob, dan jer
Tanda isim
:
-
Dlomah (masuk pada isim mufrod, jama’ mu’anats salim, dan
jama’ taksir
-
Alif (masuk pada isim tasniyah)
-
Waw (masuk pada jama’ mudzakar salim, asma’ khomsah)
Berikut ini isim-isim yang dibaca rafa’
-
Mubtada’
-
Khobar
-
Isim kana dan saudaranya
-
Khobar inna dan saudaranya
-
Fa’il
-
Na’ibul fa’il
-
Na’at dari isim yang dibaca rafa’
مبتداء
Mubtada’ adalah isim yang dibaca rafa’ yang terdapat pada
awal/permulaan jumlah, contoh : زَيْدٌ قَائِمٌ, المُمَرِّضَاتُ
رَحِيْمَاتٌ
Mubtada’ adakalanya berupa :
-
Isim mu’rob contoh : زَيْدٌ قَائِمٌ, المُمَرِّضَاتُ
رَحِيْمَاتٌ
-
Isim mabni (dlomir (kata ganti), isim isyaroh (kata tunjuk),
isim maushul (kata penghubung), isim syarat). Contoh :
هُوَ يَقُوْمُ اَمَامَ الْفَصْلِ (isim dlomir), هَذَا الْكِتَابُ, هَذَا مِنْ
فَضْلِ رَبِّي (isim isyaroh), الذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالغَيْبِ (isim maushul)
-
Mubtada’ selamanya berada pada permulaan jumlah, hanya saja
boleh kemasukan lam yang terbaca fathah (lam ibtida’) sebagaimana bolehnya
didahului huruf nafi dan huruf istifham, namun semuanya itu tidak berpengaruh
pada I’robnya, contoh :
لَزَيْدٌ اَفْضَلُ مِنْ عَمِرٍو (lam
ibtida’), مَا
نِيْلَ الْمَطَالِبِ بِالْتَّمَنِيْ ( didahului huruf nafi), هَلْ اَنْتَ نَاجِحٌ ؟
(huruf istifham)
-
Asal dari mubtada’ berupa ma’rifat, namun terkadang berupa nakiroh,
dengan ketentuan :
1)
Mubtada’ di sifati (memiliki sifat) contoh : رَجُلٌ كَرِيْمٌ عِنْدَنَا
2)
Dimudlofkan pada isim nakiroh contoh : طَالِبٌ اِحْسَانٌ وَاقِفٌ
3)
Didahului oleh huruf nafi, contoh : مَا ظَالِمٌ نَاجِحٌ
4)
Didahului oleh istifham, contoh : هَلْ رَجُلٌ فِيْكُمْ
خبر
-
Khobar adalah : kata yang menyempurnakan makna mubtada’,
contoh : المُدَرِّسُ حَاضِرٌ
-
Khobar sesuai dengan mubtada’ dalam jumlah (baik mufrod,
tasniyah, dan jama’) dan dalam macamnya (mudzakar, mu’anats) contoh : المُدَرِّسُانِ حَاضِرَانِ,
اْمُدَرِّسَتَانِ حَضِرَتَانِ, المُدَرِّسُ
حَاضِرٌ,
Ketika jama’ untuk ghoiru aqil
(tidak berakal) maka boleh khobarnya berupa mufrod mu’anats, contoh : الْجِبَالُ عَلِيَةٌ jama’ mu’anats contoh : الْجِبَالُ عَلِيَاتٌ
-
Khobar terdiri dari 3 macam :
1)
Isim dlohir (mu’rob dan mabni) contoh : الْجِبَالُ عَلِيَةٌ, اولئك الذين
اشتروا الضلالة بالهدى
2)
Sibeh jumlah (serupa dengan jumlah) الْعَامِلُ فِيْ الْمَصْنَعِ,
الحَدِيْقَةُ اَمَامَ الْمَنْزِلِ
3)
Jumlah ismiah atau fi’liyah contoh : النَّجَاحُ اَسَاسُهُ الْعَمَلُ
4)
Diperbolehkan mendahulukan Khobar dari mubtada’ dengan
catatan :
-
Ketika dikehendaki mendahulukan makna Khobar, contoh : مَمْنُوْعُ التَّدْخِيْن
-
Ketika mubtada’ dan Khobar didahului oleh huruf nafi atau
istifham sedangkan Khobar berupa sifat, contoh : اَقَائِمٌ اَنْتَ ؟
-
Ketika Khobar berupa syibeh jumlah dan mubtada’ berupa isim
ma’rifat, contoh : فِيْ التَّاَنِيْ السَّلَامَةُ
-
Wajib mendahulukan Khobar dari pada mubtada’ dengan catatan
:
1)
Khobar berupa syibeh jumlah sedangkan mubtada’ berupa
nakiroh yang tidak memiliki sifat dan juga tidak dimudlofkan, contoh : فِيْ بَيْتِنَا رَجُلٌ
2)
Khobar berupa lafadz-lafzd yang menjadi permulaan, seperti
isim istifham, contoh : مَتَى الْاِمْتِحَانُ ؟
3)
Ketika mubtada’ bertemu dengan dlomir yang kembali pada Khobar,
contoh : لِلسَّلَامِ
تَبِعَاته
-
Terkadang Khobar berbilangan, contoh : اَلرُّمَانُ حُلْوٌ حَامِضٌ
-
Khobar dibuang dalam beberapa tempat, diantaranya :
a)
Manakala Khobar jatuh setelah law ( لَوْ ), contoh : لَوْ لَا الطَّبِيْبُ مَا شَفَى
الْمَرِيْضَ
اسم كان
Isim kana
adalah setiap mubtada’ yang kemasukan kana atau salah satu dari saudaranya,
contoh : كَانَ
زَيْدٌ قَائِمًا
Saudaranya kanaa
adalah :
-
اَصْبَحَ, اَضْحَى, ظَلَّ, اَمْسى,
بَاتَ (menunjukkan waktu)
-
صَارَ (menunjukkan arti pindah)
-
لَيْسَ (untuk nafi)
-
مَا زَالَ, مَا بَرِحَ, مَا اِنْفَكَ (menunjukkan arti istimror/terus
menerus)
-
مَا دَامَ (menjelaskan waktu)
v Kana dan saudara-saudaranya
dinamakan dengan af’al naqishoh (fi’il-fi’il yang kurang) karena kana dan
saudaranya membutuhkan Khobar untuk menyempurnakan makna jumlah, sebagaimana
hal itu kanaa dan saudaranya dinamakan af’al al-nasihkoh (fi’il yang merusak)
karena kana merubah status hukum Khobar
v Amalnya kanaa adalah merafa’kan
isim dan menashabkan Khobar,
contoh : كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا (zaid sebagai isimnya kana dibaca rafa’, dan qoiman sebagai
khobarnya kanaa dibaca nashab)
خبر إن
Khobar inna adalah setiap khobar mubtada’ yang kemasukan
inna atau salah satu dari saudaranya, contoh : اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ (lafadz zid sebagai isimnya inna
dibaca nashab, lafadz qoiman sebagai khobar dibaca rafa’)
v Amalnya inna
: menashabkan isim dan merafa’kan Khobar
v Saudara inna adalah :
-
إنَّ faidahnya taukid (memperkuat), contoh : إِنَّ الْمُجِدَّ نَاجِحٌ
-
أَنَّ faidahnya taukid, inna harus didahului kalam lainnya,
contoh : يُسْعِدُنِيْ أَنَّ الصِّنَاعَةَ مُتَقَدِّمَةٌ
فِيْ بَلَدِنَا
-
كَانَ bermakna tasybih
ketika khobarnya jamid كَانَ مُحَمَّدًا اًسَدٌ ,
bermakna dzonna ketika khobarnya mustaq, contoh : كَأَنَّكَ فَاهِمٌ
-
لَكِنْ Bermakna istidroq atau menetapkan
lafadz setelahnya dengan hukum yang bertentangan اَلْكِتَابُ صَغِيْرٌ لَكِنَّهُ
مُفِيْدٌ, مَا هَذَا اَبْيَضٌ لَكِنَّهُ اَسْوَدٌ
-
لعل berfaidah roja’ (harapan), contoh :
-
لَيْتَ faidahnya tamanni (harapan) yaitu mengharapkan hasilnya
sesuatu, contoh : لَيْتَ الْشَّبَابَ يَعُدُّ يَوْمًا
-
لا faidahnya nafi, contoh : لَا سُرُوْرَ دَائِمٌ
v Khobar inna berupa :
-
Isim dlohir sebagai mana contoh diatas
-
Syibeh jumlah (serupa dengan jumlah/berupa dlorof atau jer
majrur), contoh : إِنَّ الرَّاحَةَ بَعْدَ التَّعَبِ
-
Jumlah ismiah atau fi’liyah, contoh : إنَّ الْمِصْبَاحَ ضَوْؤُهُ شَدِيْدٌ kalimat dlou’uhu syadid sebagai Khobar
inna (berupa jumlah ismiah)
لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ يوْمًا kalimat ya’udlu yauman berupa Khobar
inna (berupa dlorof)
v Boleh mendahulukan Khobar inna
ketika berupa syibeh jumlah (berupa dlorof atau jer majrur) dan isimnya ma’rifat,
contoh : إِنَّ
فِيْ التَّأَنِيْ السَّلَامَةُ
v Wajib mendahulukan Khobar inna
dengan ketentuan :
-
Ketika khobarnya berupa syibeh jumlah dan isimnya nakiroh,
contoh : إِنَّ مَعَ
العُسْرِ يُسْرًا
-
Ketika dalam isimnya inna berupa dlomir yang kembali pada khobar,
contoh : إِنَّ
فِيْ الدَّارِ صَاحِبُهَا
v Ketika مَا
bertemu dengan inna dan saudara-saudaranya maka pengamalannya batal , contoh : إنما الامم الاخلاق ما بقيت
v Hamzahnya inna akan dibaca kasrah,
dengan catatan :
-
Terdapat pada permulaan kalam, contoh : إِنَّ الْعَدْلَـــ اَسَاسُ
الْحِكَمِ
-
Jatuh setelah ucapan, contoh : قَالَ الْمُتَّهِم إِنَّي بَرِيئٌ
-
Berada pada permulaan jumlah dari shilahnya isim maushul, contoh
: جَاءَ
الّذِيْ إِنَّه نَاجِحٌ
-
Terdapat pada permulaan jumlah haliyah, contoh : قابلته و إنه يستعد للسفر
-
Jatuh setelah lafadz haitsu حيث , contoh : يسكن الناس حيث إن الراحة موفورة
فاعل
Fa’il
adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi’il, contoh : قَامَ الرَّجُلُ
v Fa’il itu adakalanya berupa :
1) Berupa isim mu’rob, sebagaimana contoh
diatas
2) Berupa isim mabni (yaitu dlomir
dlohir, dlomir mustatar, isim isyaroh, atau isim maushul), contoh : جَلَسْتُ dlomir dlohir, الرَّجُلُ حَضِرٌ dlomir mustatar, isim maushul جَاءَ الذِّيْ كُتِبَ
3) Berupa masdar mu’awal dari “أن dan fi’ilnya, atau dari أن
dan isimnya, contoh : يَنْبَغِي أَنْ تفُوْزَ
4) Ketika fa’il berupa isim tasniyah
atau jama’ maka fi’ilnya berupa mufrod, contoh : حَضَرَ الْمُدَرِّسُ, حَضَرَ
الْمُدَرِّسَانِ, حَضَرَ الْمُدَرِّسُوْنَ
5) Ketika fa’il berupa mu’anats maka fi’ilnya
bertemu dengan ta’tasnits
v Wajib membuat ta’nits fi’il Bersama
dengan fa’il, dengan catatan :
6) Ketika fa’il berupa isim dlohir mu’anats
haqiqi maka tidak digaandeng dengan fi’il. (mu’anats haqiqi adalah setiap isim
yang menunjukkan pada manusia, hewan yang beranak atau bertelur
contoh : سَافَرَتْ فَاطِمَةُ pada kata سَافَرَتْ
adalah fi’il yang digandeng dengan
ta’ fa’il
تَطَيَّرَ الْيَمَامَةُ pada kata تَطَيَّرَ adalah
fi’il yang digandeng dengan ta’ fa’il
7) Keika fa’il berupa dlomir mustatar
maka kembali pada mu’anats haqiqi atau majazi. Mu’anats majazi adalah setiap
isim yang menunjukkan mu’anats selain
haqiqi/kemu’anatsaannya tidak asli, seperti : المنضدة
( , الشمس ( matahari) meja )
Contoh : الشمس طلعت pada kata طلعت adalah fi’il yang fa’ilnya berupa dlomir mustatar
karena isimnya telah disebutkan terlebih dahulu, yaitu الشمس
8) Boleh membuat mu’anats fi’il pada
fa’il, dengan catatan :
-
Ketika fa’il berupa mu’anats haqiqi yang terpisah dengan fi’ilnya,
contoh : سافرت امس فاطمة boleh ditulis سافر امس فاطمة
-
ketika yang memisah lafadz الّا maka fi’ilnya disepikan dengan ta’, contoh : مَا نَالَ الْجَائِزَةُ إِلَّا الْفَائِزَةُ
9) Tidak disyaratkan mendatangkan fa’il setelah fi’il tetapi boleh memisah antar keduanya, contoh : اَعْجَبَنِي فِيْ الْحَدِيْقَةِ اَزْهَارُهَا
lafadz اَعْجَبَنِي adalah fi’il yang dipisah dengan fa’ilnya
yaitu اَزْهَارُهَا
نائب الفاعل
v Na’ibul fa’il adalah isim yang
dibaca rafa’ yang jatuh setelah fi’il mabni majhul dan menempati tempatnya fa’il
setelah dibuangnya, contoh : هَزَمَ الْعَدْوُ
v Fi’il itu ada kalanya berupa muta’adi
maupun lazim
v Ketika fi’il memiliki 1 maf’ul bih
sedangkan fa’ilnya dibuang, maka maf’ul bihnya dibaca rafa’ karena menggantikan
fai’il.
v Ketika fi’il jumlahnya lebih banyak
dari maf’ul bih, sedangkan fa’ilnya dibuang maka maf’ul bih yang pertama dibaca
rafa’ karena menggantikan posisinya fa’il, sedangkan maf’ul bih yang lainnya
dibaca nashob (sebagaimana asalnya). Contoh : اُعْطِيَ النَّاجِحُ جَائِزَةً
asal dari kalimat tersebut adalah اَعْطَى الْمُعَلِّمُ
النَّاجِحَ جَائِزَةً
Keterangan : النَّاجِحَ yang merupakan maf’ul bih dibaca setelah fa’ilnya
yaitu الْمُعَلِّمُ dibuang
v Ketika ada fi’il lazim, sedangkan
fa’ilnya dibuang dan fi’ilnya dimabni majhulkan maka na’ibul fa’ilnya
(pengganti fa’ilnya) boleh dijadikan Masdar atau dlorof mutashorif atau jer
majrur. Contoh : يُتَنَزَهُ فِي الْحَدَائِقِ
asalnya يَتَنَزَهُ النَّاسُ فِي
الْحَدَائِقِ
Keterangan : fi’il yang dimabni
majhulkan maka harokatnya berubah, sebagaimana keterangan di bawah
Ø Bentuk perubahan fi’il ketika
dimabni mjhulkan sebagaimana berikut
-
Fi’il madly : huruf pertama dibaca dlomah dan huruf sebelum
akhir dibaca kasrah, contoh : صَنَعَ التُّجَارُ الاَثَاثَ menjadi صُنِعَ الاَثَاثُ
Catatan : ketika huruf sebelum
akhir berupa alif, maka diganti ya’ dan huruf sebelum akhirnya dibaca kasrah.
Contoh : قَالَ الشَّاهِدُ الْحَقَّ menjadi قِيْلَ الحَقُّ
-
Fi’il mudlori’ : huruf pertama dibaca dlomah dan huruf
sebelum akhir dibaca fathah. Contoh : يَسَرَ الزَّهْرُ العَيْنَيْنِ menjadi تُسَرَّ العَيْنَانِ
Catatan : ketika huruf sebelum
akhir berupa ya’ atau wawu maka diganti alif. Contoh : يَبِيْعُ الْفَلَّاحُ الْقِطْنَ
menjadi يُبَاعُ القِطْنُ
v Ketika na’ibul fa’il berupa
tasniyah atau jama’ maka fi’ilnya dijadikan mufrod. Contoh : ضرب الولد – ضرب الولدان – ضرب الاولاد
التوابع
Tawabi’ (kata yang mengikuti) adalah setiap kalimat yang
mengikuti lafadz sebelumnya dalam segi ‘irob baik rafa’, nashab, maupun jer.
Tawabi’ (kata yang mengikuti) ada 4, yaitu : na’at, athof,
taukid, dan badal
v Na’at (sifat) adalah sifat yang
mengikuti pada isim sebelumnya,
contoh : جَاءَ الرَّجُلُ
الفَاضِلُ lafadz الفَاضِلُ
adalah sifat dari الرَّجُلُ,
Ø Sifat/naat
haqiqi harus mengikuti pada yang disifati baik dalam mufrod maupun tasniyah
atau jama’nya, mudzakar maupun mu’anatsnya, rafa’ nashab, maupun jernya. Contoh
: جَاءَتْ
السّيِّدَةُ الفَاضِلَةُ, جَاءَتْ السَيِّدَتَانِ الفَاضِلَتَانِ, جَاءَتْ
السَيِّدَاتُ الفَاضِلَاتُ
Ø Catatan :
istilah na’at adalah sifat, sedangkan man’ut adalah yang disifati. Pada contoh جَاءَ الرَّجُلُ
الفَاضِلُ na’atnya adalah الفَاضِلُ
sedangkan man’utnya adalah الرَّجُلُ
Na’at ada 2, yaitu :
-
Na’at hakiki adalah sesuatu yang menunjukkan sifat pada
diri yang diikuti, contoh : جَاءَ الرَّجُلُ الفَاضِلُ
جَاءَ الرَّجُلَانِ الفَاضِلَانِ
جَاءَ الرِّجَالُ الفَاضِلُوْنَ
-
Na’at sababi adalah sesuatu yang menunjukkan sifat pada
isim karena mengikuti isim yang di ikuti, contoh : جَاءَ الرَّجُلُ
الفَاضِلُ اَخُوْهُ
v Ketika man’ut berupa jama’ yang
tidak berakal, maka na’at haqiqinya boleh berupa mufrod mu’anats atau jama’ mu’anats.
Contoh : اَلجِبَالُ العَلِيَّةُ
atau الجِبَالُ
العَلِيَّاتُ.
v Ketika berupa na’at sababi maka
semuanya mufrad dan mengikuti pada matbu’nya (isim yang diikuti) dalam ma’rifat
nakirohnya, dan mengikuti pada isim setelahnya dalam mudzakar mu’anatsnya.
Contoh : جَاْءَ الرَّجُلُ الفَاضِلُ اَخُوْهُ
جَاءَ رَجُلَانِ فَاضِلٌ
اَخْوَاهُمَا
جَاءَ الرِّجَالُ الْفَاضِلَةُ
اَخْوَاتُهُمْ
v Na’at haqiqi ada 3 macam
a.
isim dlohir contoh : القَاهِرَةُ مَدِيْنَةٌ عَظِيْمَةٌ madinah (man’ut) berupa isim dlohir
dan ‘adhimah adalah sebagai sifat
b.
syibih jumlah contoh : لِلْحَقِّ صَوْتٌ فَوْقَ كُلَ صَوْتِ
c.
jumlah ismiah atau fi’liyah :هَذَا عَمَلٌ يُفِيْدُ
Ø Catatan : jumlah ismiyah adalah
jumlah yang terdiri dari mubtada’ dan Khobar, jumlah fi’liyah adalah jumlah
yang terdiri dari fi’il dan fa’il
Ø Jumlah tidak boleh menjadi na’at
kecuali jika man’utnya nakiroh, sebagaimana dalam contoh C
عطف
Athof adalah huruf yang berada ditengah antara lafadz yang
diikuti dan lafadz yang mengikuti,
Ø Istilah dalam athof :
-
Huruf athof : huruf yang menghubungkan antara ma’tuf dan ma’tuf
‘alaih
-
Ma’thuf : lafadz yang mengikuti ma’tuf ‘alaih
-
Ma’thuf ‘alaih : lafadz yang diikuti ma;thuf
Contoh : نجحت سعادُ و اختُها
lafadz سعادُ adalah ma’thuf, اختُهاadalah ma'tuf 'alaih, dan و adalah huruf 'athof
Ø Huruf ‘athof ada 9, yaitu : واو, فاء, ثم, او, ام, لا, لكن, بل, حتى
Ø Faidah huruf athof :
-
واو
muthlakul jam'I, contoh : جَاءَ محمدٌ و حسنٌ و سعيدٌ
-
فاء tartib (urut) dan ta’qib (mengiringi),
contoh : دَخَلَ زَيْدٌ فَعضمْرٌو
-
ثم
tartib (urut) ), contoh : مَات الرَّشِيْدُ ثُمَّ الْمَأمُوِنُ
-
اوtakhyir (memilih) atau syak (ragu), contoh : نَقَلَ الْخَبَرَ مُحمدٌ او عليٌ
-
ام tholab ta’yin (minta kepastian), contoh : هَذَا الْمَقَالُ عَمْرٍو اَمْ مُحَمُودٍ
-
لا menafikan hukum, contoh : نَضَجَ الْبِطِيْخُ لا العِنَبُ
-
لكن istidrok (menyusuli), contoh : مَا نَجِحَ عَلِي لَكِنْ اَخُوْهُ
-
بل ‘udul (memindah hukum), contoh : ظَهَرَ عَلَى الْاَمْوَاجِ زَوْرَقٌ
بَلْ بَاخِرَةٌ
-
حتى ghoyah (Puncak / tujuan akhir), contoh : اَكَلْتُ
سَمَكَةَ حَتَّى رَأْسَهَا
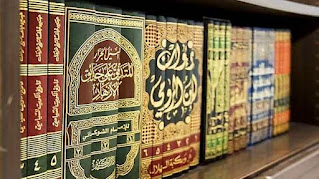







Comments
Post a Comment